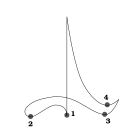TINJAUAN SEJARAH MUSIK
Perkembangan musik klasik dapat dikelompokkan dengan
berbagai sistem. Sebagai contoh ialah yang mengacu pada
perkembangan tekstur musikal, seperti periodesasi yang di buat oleh
Ewen (1963:7-13): Era Polifonik (1200-1650), Masa Kelahiran Homofonik
(abad ke-17), Periode Klasik (abad ke-18 hingga permulaan abad ke-19)
Periode Roantik (abad ke-19) dan Periode Modern (abad ke-20).
Sementara itu Stein (1963) merdasarkan periodesasi historis musik klasik
atas prosedur komposisi dan bentuk musik. Menurut sitem tersebut
taksonomi historis musik klasik adalah sebagai berikut: Era Abad
Pertengahan (300-1000), Romanesque (1000-1150), Ars Antiqua (1150-
1300), Ars Nova (1300-1400), Renaisans Awal (1400-1500), Renaisans
Tinggi (1500-1600), Barok (1600-1750), Rococo (1725-1778), Klasikisme
(1750-1827), Romantikisme (1800-1900), Impresionisme (1880-1918),
dan Abad ke-20 (1900 hingga sekarang). Walaupun demikian, dalam bab
ini periodisasi yang disampaikan ialah Era Kuno (Sebelum 600), Era
Abad Pertengahan (600-1450), Era Renaisans (1450-1600), Era Barok
(1600-1750), Era Klasik (1750-1820), Era Romantik (1820-1900), dan Era
Kontemporer (1900-Sekarang).
Era Kuno (Antiquity) (- 500)
Sejarah Terbentuknya Musik Barat
Musik Barat Awal terbentuk oleh tiga komponen budaya meliputi
tradisi-tradisi yang tidak sepenuhnya Eropa: Pertama, Timur Tengah
dan Mesir Kuno (daerah Mesopotamia di sekitar sungai Tigris dan
Euphrate yang didiami suku-suku bangsa Sumeria, Babylonia, dan
Assyria) meninggalkan artefak gambar-gambar instrumen musik yang
sudah lengkap (idiofon, aerofon, kordofon, dan membranofon) untuk
memainkan himne yang diukir pada batu tahun 800 SM. Lima ratus tahun
kemudian Bangsa Mesir melakukan hal yang sama, sedangkan bangsa
Yahudi tercatat sejak tahun 2000 SM dan didokumentasikan dalam Kitab
Perjanjian Lama yang lebih berkembang karena kemudian diadobsi dan
diadaptasikan dalam liturgi agama Kristen kemudian. Tradisi peribadatan
Yahudi di synagoge (kuil) berupa gaya menyanyi silabis dan melismatis
hingga kini tetap digunakan di seluruh dunia.
Kedua, Yunani Kuno, merupakan budaya yang paling
berpengaruh pada perkembangan musik di Barat melalui bangsa Romawi
yang menaklukkan mereka tetapi sekaligus banyak mengadobsi
budayanya. Sejarah Yunani baru mulai sekitar tahun 1000 SM tetapi
segera mempengaruhi bangsa-bangsa sekitarnya. Dua dewa yang paling
dipuja bangsa Yunani Kuno adalah Apollo dan Dionysus—kelak menjadi prototipe dua kutub aliran estetika yang saling berlawanan yakni klasik
dan romantik. Pemuja Apollo, memainkan instrumen musik berdawai
kithara sejenis lyre adalah kaum yang berwatak objektif terhadap
ekspresi, sederhana, dan jernih. Sebaliknya pengikut Dionysus suka
memainkan instrumen tiup aulos, bersifat subjektif, emosional, dan
berhawa nafsu besar. Doktrin etos seperti yang dijelaskan filsuf Plato dan
Aristoteles meyakini bahwa musik memberikan efek langsung pada
perilaku seseorang yang mendengarkannya. Akibatnya, sistem sosial dan
politik menjadi belit-membelit dengan musik, pendidikan berfokus pada
musik dan olahraga senam (musica dan gymnastica), bahkan untuk
membentuk tatanan fundamental masyarakat dilakukan rasionalisasi
musik seperti: penalaan nada, memilih instrumen musik, mencipta modus
dan ritme-ritme. Ahli matematik Pythagoras menjadi orang pertama yang
meneliti perbandingan-perbandingan getaran dawai dan menetapkan
urutan nada-nada yang hingga kini menjadi dasar sistem musik diatonik.
Ketiga, Romawi Kuno, bilamana budaya musikal wilayah
Mediterania timur dicangkok-kan ke dalam wilayah Mediterania barat oleh
kembalinya serdadu-serdau Romawi, maka modifikasi dengan berbagai
selera dan tradisi-tradisi lokal yang ada tak bisa dihindarkan. Modifikasi
nyatanya bahkan hanya lebih menyederhanakan saja dari model-model
yang diadobsi. Tangga nada diatonik (tujuh nada) dijadikan standar
menggantikan struktur-struktur kromatik dan enharmonik dari sistem
musik Yunani. Romawi tidak memiliki kekayaan warisan musikal berupa:
teori akustik, konsep modus, pengelompokan ritme, organologi instrumen
musik, sistem notasi yang meliputi pitch dan durasi, dan banyak repertoar
berupa melodi-melodi yang digunakan untuk contoh-contoh pada
komposisi selanjutnya.
Sejarah Musik Era Abad Pertengahan (Medieval Era) 600-1450
Meliputi suatu periode masa yang paling panjang terkait dengan
semua kehidupan dan seni untuk pelayanan gereja. Musik untuk
keperluan ibadat, sebagai alat utama untuk memahami karya-karya
Tuhan Allah. Mewarisi modus-modus Yunani, bangsa Romawi yang
kristen mengembangkan modus-modus gereja sebagai sistem tangga
nada yang hingga kini masih digunakan dalam berbagai peribadatan
kristen. Standarisasi dalam berbagai lapangan pengetahuan juga terjadi
dalam musik, biarawan dan teoretikus musik Guido d’Arezzo (ca. 997 –
ca. 1050) merancang sistem menyanyi yang dinamakan ’solmisasi’.
Pemimpin gereja Paus Gregorius I mengatur penggunaan lagu-lagu
pujian untuk peribadatan gereja yang dikenal dengan Gregorian chant. Gaya polifoni sebagai teknologi komposisi yang menggabungkan
dua alur melodi atau lebih memperkaya rasa keindahan musikal
dibandingkan gaya monofon sebelumnya dan cikal-bakal harmoni. Pusat
musik abad ke-14 adalah Italy dengan komposer-komposer penting
seperti Francisco Landini, Giovanni da Cascia, dan Jacopo da Bologna.
Untuk pertama kali di Paris para pencipta musik Léonin dan Perotin yang
notabene adalah biarawan Katedral Notre-Dame disebut sebagai
komposer-komposer ”Aliran Notre-Dame” (The Notre-Dame School).
Sebuah risalah penting berjudul Ars Nova (Seni Baru) oleh Philippe de
Vitry muncul lebih awal pada abad ke-14 dan sekaligus menunjukkan
bahwa seni yang berkembang sebelumnya menjadi kuno.
Sejarah Musik Era Renaisans (1450-1600)
Berwatak klasik, pengekangan, menahan diri, dan kalem. Selain
tertarik pada kebudayaan Yunani Kuno, juga berkembang humanisme
khususnya di Italia dan fundamentalisme di Eropa Utara, tetapi sarat
dengan penemuan ilmiah. Kebudayaan termasuk musik berkembang baik
di dalam maupun di luar gereja. Manusia seperti telah menemukan
kembali jati dirinya terutama tampak pada idealisme kaum Protestan
yang meyakini bahwa manusia bisa berhubungan langsung dengan
Tuhan-nya. Melodi dan tekstur musik masih menggunakan modus-modus
sebelumnya, tetapi akord-akord mulai disusun dengan cara
menghubungkan melodi-melodi yang menghasilkan konsonan atau
disonan. Selain musik vokal, era ini ditandai mulainya komposisi solo
dengan iringan ansambel instrumental. Selama abad ke-16 musik
instrumental merangkak naik cepat terkait dengan perkembangan teknik-
teknik permainan instrumen yang idiomatis seperti ritme-ritme beraksen
kuat, nada-nada yang diulang-ulang, wilayah nada semakin luas dan
panjang, nada-nada yang ditahan dan frase-frase, dan banyak
ornamentasi melodi.
Renaisans dapat diartikan sebagai periode dalam Sejarah Eropa
Barat dimana manusia mulai melakukan eksplorasi terhadap dunia, baik
melalui perjalanan atau penjelajahan ke Timur maupun ke Selatan
belahan bumi, tetapi mereka juga gemar mengembangkan ilmu
pengetahuan dan kesenian. Oleh karena pikiran manusia menjadi
semakin bebas, maka musik sekuler mulai muncul dan berkembang pula
musik-musik instrumental yang semula kurang mendapatkan tempat di
lingkungan tradisi gereja. Tetapi musik gereja tetap sangat penting dan
gaya polifonik vokal sangat berkembang pada periode ini. Komposer-
komposer terpenting ialah Josquin des Prés, Orlandus Lassus, William
Sejarah MusikEra Barok (1600-1750)
Periode waktu musik Barok yang juga dikenal sebagai awal suatu
masa paling dramatik dalam sejarah musik, dikatakan sebagai mulainya
era tonal, tetapi totalitas musik yang menggunakan tangga nada diatonik
sebenarnya berlangsung hingga pada awal abad ke-20, selebihnya musik
modern mulai banyak yang meninggalkan sistem diatonik itu. Sekalipun
kata Perancis Baroque; Inggris/Jerman: Barock; Italy: Barocco—semua
menunjuk pada kata sifat ’bizaree’ (aneh, ajaib, dan ganjil)—pada
mulanya berkonotasi buruk, digunakan untuk tujuan menghina,
merendahkan, dan abnormal; tetapi definisinya semakin menjadi positif,
agung, dramatik, dan bahkan mengandung spirit kuat dalam seni. Spirit
itu diperlukan untuk mengembangkan kekayaan musikal dan menumbuhkan dengan cepat teknik-teknik yang diperlukan. Dua gaya
musik yang terpenting adalah gaya antik (prima prattica, stile antico) dan
(sconda prattica, stile moderno) yang lebih teatrikal daripada yang
pertama. Periode pertama era Barok sebagai awal ditandai dengan
penerapan unsur dramatik pada musik terutama pada operan dan
oratorio, tetapi juga pada musik instrumental dengan menambahkan
unsur-unsur dinamik seperti forte-piano (keras-lembut).
Di Italy ada komposer-komposer antara lain Giulio Caccini,
Jacopo Peri, Claudio Monteverdi, dan Pietro Francesco
Cavalli; di Perancis ialah Jean Baptiste Lully; dan di Jerman Heinrich
Schütz. Periode kedua ditandai oleh adanya unsur keseimbangan
harmonik dan polifonik pada komposisi-komposisi Barok yang dilakukan
oleh para komposer Italy Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Allesandro
Scarlatti, dan Domenico Scarlatti; Inggris Henry Purcell, komposer
Perancis Francois Couperin, Jerman Johann Sebastian Bach, dan
George Frideric Handel. Musik Barok menyumbang bagi kesempurnaan
sistem musik Barat dengan sistem tonalitas yang berbasis perkuncian,
memformulasikan nada-nada menjadi akord-akord, interrelasi melodi dan
akord dalam tangga nada mayor atau minor—menjadikan musik diatonik
bisa diterima mendunia. Dua gaya musikal yang sangat berbeda dari
Renaisans adalah gaya musik concertato dan basso continuo.
Gaya pertama menerapkan teknik kontras, kombinasi, dan
alternasi antara solo dan iringan; sedangkan yang kedua teknik
menggarap iringan musik berbasis nada-nada bas (nada paling bawah).
Dua gaya itu banyak digunakan dalam komposisi instrumental yang
menjadikan era ini merupakan masa gemilang musik instrumental seperti
jenis musik ”sonata” dan ”concerto”. Pusat-pusat musik Barok dan para
komposernya adalah Italia, Perancis, Inggris, dan Jerman; semua
menghasilkan beraneka ragam repertoar musik vokal dan instrumental
seperti sinfonia, overture, opera, sonata da chiesa, dan sonata da
camera. Musik hiburan (entertainment music) secara bertahap mulai
berkembang baik secara kualitas maupun kuantitasnya dan memperkaya
musik gereja yang sudah ada. Mulai tahun 1700 beberapa bentuk musik
berbeda muncul seperti solo sonata, trio sonata, suita tarian, dan
concerto grosso.
Sejarah Musik Era Klasik (1750-1820)
Seperti yang terjadi pada era Renaisans, sebenarnya cukup sulit
mendefinisikan era ini sekalipun menggunakan tinjauan periode waktu,
perbedaan gaya-gaya musikal, perilaku estetik, idealisme, atau bahkan
norma-norma yang ditetapkan. Cara paling mudah memahami era Klasik
Byrd, dan Giovanni Pierluigi da Palestrina. ialah dengan memahami klasikisme sebagai idealisme para pemuja dewa
Apollo era Yunani Kuno. Era ini mewarisi dan mengembangkan
klasikisme secara total melalui pikiran positif, sikap tenang, seimbang
antara rasio dan rasa, dan struktur yang jernih. Jika Apollo adalah dewa
keadilan, keindahan, seni, musik, dan sebagai personifikasi dari watak
tenang dan seimbang (hamonious tranquility); maka teori penting tentang
Apollo dikembangkan Nietzsche yang mengatakan bahwa Apollo adalah
dewa kebijaksanaan, pikiran analitis, pembentuk kepribadian, refleksi diri,
dan pemahaman—yang dilawan oleh Dionysus sebagai dewa yang
melahirkan prototipe romantikisme.
Kata “klasik” bermakna sesuatu yang ber-‘kelas’ tinggi, bukan
sesuatu yang berkualitas sembarangan. Musik klasik (semua musik
serius) termasuk dalam kategori itu, tetapi era Klasik tidak mendadak
menemukan jati-dirinya melainkan dimulai oleh gaya rokoko yang riang
(galant style) khususnya di Perancis dan gaya sentimental
(empfindsamer stil) yang dikembangkan pada tahun 1750 hingga 1760-
an di Jerman. Perancis menyumbang obsesi kejernihan (lightness),
keanggunan (gracefulness), dan hiasan (decoration); sedangkan Jerman
lebih senang pada masalah rasa (sensibilities). Di Jerman suatu gerakan
kesenian yang penting adalah Sturm und Drang (”Storm and Stress”,
”Badai dan Stres”) muncul selama tahun 1770 hingga 1780-an dipelopori
oleh pujangga besar Goethe dan kawan-kawan yang mengajak agar lebih
meningkatkan ekspresi personal dan menggunakan repertoar bangsa
sendiri dalam karya-karya seni—Jerman.
Perubahan fundamental gaya musikal Klasik dari Barok
diinspirasikan oleh Rokoko yang memurnikan kembali idealisme klasik
Yunani Kuno oleh para komposer hebat seperti Joseph Haydn, Wolgang
Amadeus Mozart, Christoph Willibald Gluck, dan Ludwig van Beethoven.
Untuk pertama kali dalam sejarah musik bahwa musik instrumental lebih
penting daripada musik vokal. Orkestra dan musik kamar seperti kuartet,
kuintet, dan trio piano—dijadikan standar dan menggantikan dominasi
ansambel-ansambel Barok. Polifoni digantikan gaya homofoni yang
membedakan fungsi melodi dan progresi akord-akord sebagai iringan.
Bentuk musik (musical form) terpenting adalah bentuk sonata (sonata
form) yang digunakan pada simfoni, sonata, dan konserto.
Suatu gerakan kesenian yang penting ialah Sturm und Drang
(”Storm and Stress”, ”Badai dan Stres”) muncul di Jerman dipelopori oleh
pujangga besar Goethe dan kawan-kawan, mengajak seniman agar lebih
meningkatkan ekspresi personal dan menggunakan repertoar sendiri
dalam karya-karya seni. Melalui gerakan kebudayaan itu para pujangga
menggugah kesadaran cinta tanah air atau nasionalisme bagi bangsa
Jerman melalui perhatian mereka pada karya-karya seni bangsa sendiri.
Sejarah Musik Era Romantik (1820-1900)
Komposer-komposer Jerman seperti Beethoven merespon
gerakan Sturm und Drang dan menjadikan pergantian gaya musikal dan
sikap estetik yang lebih personal, nasionalistik, bebas, dan menjadikan
ciri khas Romantik. Batasan romantik berasal dari sastra Jerman pada
akhir abad ke-18, seorang penulis Franco-Swiss bernama Mme de Staël
mengaitkan gagasan-gagasan baru dengan gerakan yang terjadi pada
tahun 1813 sebagai sesuatu yang asli, modern, populer, natural, religius,
dan pemberlakuan institusi-institusi sosial. Maka musik Romantik
berbeda dari gaya sebelumnya dan acapkali dikatakan berlawanan
dengan Klasik karena wataknya yang emosional, subjektif, nasionalis,
individual, eksotis, melarikan diri, nafsu bebas, dan bahkan tidak rasional.
Sifat-sifat gaya romantik
Sifat-sifat gaya romantik sangat ditentukan oleh upaya para
komposer yang memperkaya sumber-sumber inspirasi dan sumber-
sumber material bagi komposisi mereka. Orkestra, musik piano, solo
vokal dengan iringan piano, dan opera dijadikan sebagai jenis-jenis musik
utama, tetapi musik kamar dan musik vokal pujian agak dipinggirkan.
Metrik genap dan metrik gasal dijadikan sebagai basis metrik musik,
tetapi terkadang dilakukan juga eksperimen-eksperimen menggabungkan
keduanya secara tidak biasa. Ritme diakui sebagai suatu inti yang
penting dari masalah ekspresi dalam musik. Gaya melodi ditekankan
berasal dari gaya menyanyi dengan ciri panjang dan alur-alur lirik. Di sisi
lain kemungkinan-kemungkinan baru secara idiomatis pada perwatakan
instrumen digali dan dikembangkan. Elemen-elemen harmoni dan tonal
terus-menerus dikembangkan selama abad itu, dengan kromatikisme,
sonoritas diperkaya misalnya dengan akord tujuh dan akord sembilan,
dan bunyi-bunyi yang nonharmonis banyak digunakan secara lebih
bebas. Modulasi-modulasi semakin menjauh dari tonalnya, tetapi musik
masih berpusat pada melodi dan harmoni.
Beethoven adalah seorang figur transisional yang menghantarkan
gaya Klasik abad ke-18 menuju gaya Romantik abad ke-19. Ia adalah
komposer yang paling fenomenal dalam sejarah musik diatonik karena
kegigihannya dalam menunjukkan personalitas dan watak pribadi melalui
komposisi-komposisinya. Terinspirasi oleh adanya kekuatan-kekuatan
revolusioner pada masanya, terutama Revolusi Perancis, ia
mendeklarasikan sendiri sebagai pembaharu artistik yang merdeka,
bebas dari pengaruh kekuasaan atau patron tertentu. Pada awalnya ia
mencipta musik demi memenuhi pesanan dan imbalan finansial, tetapi
kemudian pada tahun 1820 ia mulai mendeklarasikan kebebasan dirinya
dalam mencipta musik dan hanya menulis musik jika digerakkan oleh
imajinasi dan kata hatinyas saja. Ia telah menetapkan aspek-aspek
seperti individualitas, subjektivitas, dan ekspresi emosional sebagai standar pada komposer-komposer Romantik. Kemerdekaan atau
kebebasan (freedom) adalah kata yang melekat pada komposer paling
fenomenal ini, ia berani melawan Kaisar Napoleon Bonaparte melalui
Simfoni No. 3 Eroica yang kemudian menjadi tonggak sejarah musik
Romantik. Beethoven tampil sebagai pujangga musik dunia yang mampu
menembus batas-batas kultur Barat.
Kontras dengan eksperimen-eksperimen Schoenberg dan
Stravinsky tersebut selama dekade kedua abad ke-20 muncul aliran yang
ingin kembali kepada idaman-idaman estetika akhir abad ke-18 dan
kemudian dinaman Neoklasik. Tokoh-tokohnya ialah Paul Hindemith,
Béla Bartok, dan Sergey Prokoviev dan Alban Berg. Aliran ini berwatak
terbebas dari muatan emosional, penyederhanaan material-material,
struktur dan tekstur; dan lebih mementingkan garis-garis melodi
kontrapungtis daripada warna harmonik atau instrumental. Neoklasik
diteruskan sebagai tren utama hingga sekitar tahun 1920 dan Perang
Dunia II berlangsung, teknik-teknik ekspetimental dikenalkan selama
dekade kedua abad ini secara bertahap dimurnikan kembali, dimodifikasi,
dan digabungkan ke dalam perbendaharaan istilah musikal yang diterima
umum.
Pasca Perang Dunia II ditandai oleh dua sikap artistik utama yang
cenderung menggabungkan unsur-unsur yang ada, Anton von Webern
membawa komposisi serial secara lebih ekstrim secara ketrampilan dan
intelektual yang berorientasi kepada Klasikisme daripada
Ekspresionisme. Stravinsky, anggota tertua dari kelompok Neoklasik,
mulai melakukan ekperimen dengan Serialisme. Musik Avant-garde mulai
dikembangkan dengan teknik-teknik yang memungkinkan menggunakan
unsur elektronika.